Pendidikan
Terkesan dengan Sistem Pembelajaran UT, Kunjungan Universitas Internasional Al-Mustafa Mengisyaratkan Kemitraan Kolaboratif yang Menjanjikan
Dipublikasikan oleh Muhammad Armando Mahendra pada 18 Februari 2025
Universitas Terbuka (UT) merupakan perguruan tinggi negeri ke-45 dan pelopor penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Terbuka dan Jarak Jauh di Indonesia. Saat ini UT memiliki populasi mahasiswa aktif sebanyak 550.052 orang dengan target sebanyak 750.000 orang pada akhir tahun 2024.
Pada tanggal 1 April 2024, UT berkesempatan menerima tamu dari Al-Mustafa International University (MIU), Republik Islam Iran, yang telah berdiri selama 40 tahun dan beroperasi di lebih dari 60 negara dengan jumlah mahasiswa lebih dari 50.000 orang. Dengan divisi pembelajaran jarak jauhnya, Universitas Terbuka Al-Mustafa (MOU), MIU mengunjungi UT untuk melakukan benchmarking dan wawasan tentang pembelajaran jarak jauh. Pertemuan antara UT dan MIU berlangsung di Ruang Brahma Gedung Prof Setijadi Universitas Terbuka.

Sumber: www.ut.ac.id
Rektor UT, Prof. Ojat Darojat, M.Bus., Ph.D., mengawali pertemuan dengan menyambut delegasi MIU dan memperkenalkan UT sebagai universitas penyelenggara pendidikan inklusif untuk pemerataan pendidikan tinggi di seluruh Indonesia. Dalam sambutannya, Rektor juga menyampaikan bahwa UT memperluas kehadiran internasionalnya melalui kerjasama dengan institusi luar negeri dan posisinya sebagai presiden Asian Association of Open University (AAOU).
Sementara itu, Direktur MIU untuk Asia Tenggara, Prof.Dr.Hossein Muttaghi, mengungkapkan kekagumannya terhadap sistem pembelajaran UT dalam sambutannya. Ia juga memperkenalkan profil MIU sebagai universitas yang memadukan studi humaniora dan agama. Dijelaskan pula perkembangan MOU sebagai lembaga pembelajaran jarak jauh yang berencana menerapkan pembelajaran asynchronous. Ia menyatakan kesediaannya untuk berkolaborasi dengan UT dalam program double-degree di masa depan.

Sumber: www.ut.ac.id
Pembahasan antara UT dan MIU pada tanggal 1 April 2024 secara garis besar mencakup kerjasama kedua pihak dan sistem pembelajaran di UT. Prof Ojat memaparkan kerangka umum sistem pendidikan tinggi jarak jauh UT yang menyediakan akses pembelajaran melalui berbagai media seperti Buku/Modul Perkuliahan interaktif cetak dan digital, UT TV, Radio UT, dan lain-lain.
Hal ini menjadi inspirasi bagi Prof. Hossein untuk mengimplementasikan MOU. Ia juga menyampaikan ketertarikannya untuk menjalin kerjasama dengan program terbaru UT yaitu Sarjana Pendidikan Islam, sebagai langkah awal mewujudkan kerjasama program double-degree tersebut.
Usai diskusi bersama, dilakukan pertukaran cinderamata dan foto, serta kunjungan ke unit operasional UT. Kunjungan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan membina kerjasama lebih lanjut antara kedua universitas.
Disadur dari: www.ut.ac.id
Pendidikan
Pembelajaran Jarak Jauh: Panduan Utama untuk Pembelajaran Online
Dipublikasikan oleh Muhammad Armando Mahendra pada 18 Februari 2025
Apa itu pembelajaran jarak jauh?
Pembelajaran jarak jauh adalah proses pendidikan di mana siswa menerima pengajaran melalui kelas online, rekaman video, konferensi video, atau media teknologi audio/visual lainnya. Hal ini memungkinkan orang untuk menerima pendidikan tanpa harus hadir secara fisik di ruang kelas.
Program pembelajaran jarak jauh yang dirancang dengan baik dapat menjadi cara yang sangat nyaman dan efektif untuk memperoleh lebih banyak pendidikan. Hal ini mungkin tampak sulit tanpa siswa dan guru berinteraksi di dalam kelas, namun orang-orang yang mengikuti program pembelajaran jarak jauh dapat belajar jauh dari ruang kelas seperti halnya di dalam kelas.
Pembelajaran jarak jauh dan pendidikan adalah istilah yang dapat dipertukarkan. Pembelajaran jarak jauh bukanlah sebuah fenomena baru. Asal usul pembelajaran jarak jauh dapat ditelusuri kembali ke munculnya sistem pos modern dan produksi massal publikasi cetak, yang memungkinkan penyebaran informasi dengan cepat ke seluruh dunia.
Mengapa pembelajaran jarak jauh?
Pembelajaran jarak jauh telah membuat pendidikan lebih mudah diakses oleh kelompok masyarakat yang lebih besar. Ini adalah cara mudah untuk memperoleh pengalaman kerja sambil menyelesaikan perguruan tinggi atau pelatihan kejuruan lainnya. Banyak organisasi, seperti militer, perusahaan besar, dan lembaga pemerintah mengandalkan pendidikan jarak jauh untuk melatih anggota militer dan karyawannya. Pendidikan juga berubah seiring dengan revolusi teknologi komunikasi dalam masyarakat.
Dalam kebanyakan kasus, pendidikan atau pelatihan khusus merupakan persyaratan untuk sebagian besar pekerjaan bergaji tinggi. Ketersediaan Internet telah meningkatkan jumlah kursus online. Kursus-kursus ini ditawarkan di perguruan tinggi online, seperti Universitas Argosy, Universitas Phoenix, Universitas Capella, dan Universitas Kaplan.
Siapa yang menggunakan pembelajaran jarak jauh?
Saat ini semakin banyak siswa yang memanfaatkan program pembelajaran jarak jauh. Para profesional yang bekerja, siswa sekolah menengah, dan bahkan mahasiswa tradisional mendaftar di kelas pembelajaran jarak jauh. Perusahaan dan organisasi lain sering memanfaatkan program pembelajaran jarak jauh untuk melatih karyawan. Berikut adalah beberapa alasan orang mengikuti program pembelajaran jarak jauh:
- Siswa yang tinggal di daerah pedesaan atau mereka yang tidak dapat menghadiri kelas tradisional memanfaatkan pembelajaran jarak jauh.
- Siswa dari seluruh dunia dapat mendaftar di kursus online yang ditawarkan di perguruan tinggi tertentu.
- Perusahaan memanfaatkan program pembelajaran jarak jauh untuk melatih karyawannya, terutama yang bekerja di wilayah yang jauh.
Pembelajaran jarak jauh sangat fleksibel
Meskipun pembelajaran jarak jauh dapat disesuaikan dengan jadwal siapa pun, siswa harus mengambil inisiatif untuk belajar dan menyelesaikan tugas kursus mereka. Program pembelajaran jarak jauh tidak mudah atau otomatis, sehingga siswa yang malas mungkin tidak akan berhasil menyelesaikan kursus yang mereka ikuti. Namun, siswa yang sibuk atau memiliki banyak tanggung jawab pun harus meluangkan waktu untuk belajar karena fleksibilitas program ini.
Teknologi apa yang digunakan untuk pembelajaran jarak jauh online?
Berbagai jenis teknologi digunakan untuk meningkatkan pembelajaran online. Program komputer khusus, Internet berkecepatan tinggi, dan teknologi penyiaran webcam hanyalah beberapa dari teknologi modern yang digunakan dalam pembelajaran jarak jauh. Akibatnya, kesempatan belajar yang tidak pernah ada bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau pedesaan dapat memperoleh pendidikan perguruan tinggi atau pelatihan kerja khusus. Bukan hal yang aneh bagi seorang siswa yang tinggal di daerah pedesaan South Dakota untuk menyelesaikan kursus yang ditawarkan oleh sebuah perguruan tinggi di California.
Siswa sering berinteraksi dengan guru menggunakan konferensi video, satelit, dan teknologi Internet. Mereka juga dapat berkomunikasi dengan siswa lain yang terdaftar pada mata kuliah yang sama menggunakan teknologi telekomunikasi modern.
Karena siswa dapat menyelesaikan kursus di mana pun Internet dapat diakses, banyak siswa yang sering meluangkan waktu selama istirahat kerja atau saat menginap di hotel selama perjalanan bisnis untuk menyelesaikan tugas sekolah mereka. Fleksibilitas pembelajaran jarak jauh adalah salah satu daya tarik utama program ini.
Seperti apa pengalaman pembelajaran jarak jauh online?
Karena pembelajaran jarak jauh perlahan menjadi cara yang populer untuk menyelesaikan kuliah atau pelatihan kerja, banyak orang masih ragu mengenai hal tersebut. Perincian yang diberikan di bawah ini akan memberikan gambaran kepada mereka yang mempertimbangkan pembelajaran jarak jauh tentang seperti apa:
- Siswa biasanya berinteraksi dengan teman sekelas dan guru di ruang obrolan dan layanan pesan instan lainnya. Hal ini memungkinkan untuk mengajukan pertanyaan dan berbagi komentar tanpa harus duduk di ruang kelas. Ceramah guru sering kali disiarkan secara online, dan banyak siswa serta guru tetap berhubungan melalui teknologi panggilan konferensi.
- Kerja kelompok diselesaikan di ruang obrolan dan ruang khusus di situs web. Siswa juga menggunakan email, pesan instan, dan teknologi penyiaran web untuk mendiskusikan ide proyek dengan teman sekelas.
- Tugas kursus yang diselesaikan oleh siswa diselesaikan di situs web atau diserahkan sebagai lampiran email. Siswa biasanya tidak diizinkan untuk mengirimkan pekerjaan yang diselesaikan di situs web setelah tanggal jatuh tempo.
- Sebagian besar bahan referensi, seperti dokumen dan buku, dapat diakses secara online oleh siswa. Akibatnya, siswa biasanya tidak perlu mengunjungi perpustakaan untuk menyelesaikan penelitian tradisional. Banyak buku yang dibutuhkan siswa dipindai dan ditempatkan secara online.
- Pertanyaan untuk instruktur dapat ditanyakan melalui telepon, email, atau di ruang obrolan. Teknologi pesan instan menjadi cara yang sangat populer bagi siswa dan guru untuk berinteraksi.
Para profesional yang bekerja, ibu rumah tangga, dan orang lain yang tidak dapat mengikuti kuliah di kampus memanfaatkan program pembelajaran jarak jauh untuk memperoleh lebih banyak pendidikan atau pelatihan kerja.
Memilih sekolah pembelajaran jarak jauh
Pembelajaran jarak jauh telah ada selama berabad-abad melalui surat tradisional dan sarana kreatif lainnya, namun pendidikan online masih merupakan bidang yang relatif baru. Meski teknologinya berbeda, namun misi pendidikan dan standar akademiknya sama dengan pendidikan tradisional: menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Banyak sekolah online melakukan hal tersebut, sementara yang lain hanya sekedar penggilingan gelar atau penipuan. Dan tentu saja, ada banyak variasi di tengahnya.
Disadur dari: www.educationcorner.com
Pendidikan
Apa itu Pembelajaran Online? Sejarah Singkat dan Manfaat
Dipublikasikan oleh Muhammad Armando Mahendra pada 18 Februari 2025
Pengertian pembelajaran online
Pembelajaran online, juga disebut sebagai e-learning , pembelajaran digital atau bahkan terkadang pembelajaran virtual, mencakup spektrum luas aktivitas pendidikan yang difasilitasi melalui teknologi digital.
Pembelajaran online adalah suatu bentuk pendidikan di mana pengajaran dan pembelajaran berlangsung melalui internet dan melalui alat atau platform pembelajaran digital seperti platform pembelajaran online , dan sistem manajemen pembelajaran (LMS) .
Dibandingkan dengan interaksi tatap muka tradisional di ruang kelas fisik, pembelajaran online sangat bergantung pada teknologi untuk menyampaikan konten pendidikan, memfasilitasi komunikasi antara instruktur dan peserta didik, dan menilai kemajuan peserta didik.
Sejarah pembelajaran online
Akar pembelajaran online sangat terkait dengan perkembangan teknologi komputasi dan Internet. Evolusinya dapat ditelusuri kembali ke pertengahan abad ke-20 ketika para pionir mulai mengeksplorasi potensi teknologi untuk meningkatkan pengalaman pendidikan.
Untuk lebih memahami pembelajaran online dan bagaimana pembelajaran online menjadi seperti sekarang ini, mari kita kembali ke masa lalu untuk melihat tonggak penting pembelajaran online.
- Periode/Tahun Perkembangan Penting dalam Pembelajaran Online
- Tahun 1960-an Awal mula pelatihan berbasis komputer (CBT) dengan menggunakan komputer mainframe.
- Tahun 1970-an Pengenalan sistem PLATO untuk instruksi berbantuan komputer.
- Tahun 1980-an Munculnya telekonferensi dan pembelajaran jarak jauh berbasis satelit.
- Tahun 1990-an Munculnya World Wide Web; lahirnya era Internet modern.
- 1994 Kursus online pertama diluncurkan oleh University of Toronto.
- 1997 Peluncuran Blackboard, pionir dalam sistem manajemen kursus online.
- 1999 Istilah “e-learning” digunakan pada saat itu dalam konteks profesional oleh Elliott Masie pada konferensi TechLearn di Disney World.
- 2002 Massachusetts Institute of Technology (MIT) meluncurkan OpenCourseWare, membuat materi kursus tersedia secara online secara gratis.
- 2005 YouTube didirikan, menyediakan platform untuk konten video pendidikan.
- 2006 Pengenalan Kursus Online Terbuka Besar-besaran (MOOCs) oleh universitas-universitas Kanada dan Amerika.
- 2015 Pengenalan kamp pelatihan coding online untuk pengembangan keterampilan teknis.
- 2016 Bangkitnya pembelajaran seluler seiring dengan menjamurnya ponsel pintar dan tablet.
- 2019 Pertumbuhan platform pembelajaran adaptif, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa.
- 2020 Ekspansi pembelajaran daring yang pesat karena pandemi COVID-19, menyoroti pentingnya dan aksesibilitasnya.
- Hadiah Inovasi berkelanjutan dengan teknologi virtual reality (VR), augmented reality (AR), dan kecerdasan buatan (AI) di bidang pendidikan.
Manfaat utama pembelajaran online
Pembelajaran online menawarkan beberapa keuntungan , termasuk aksesibilitas bagi pelajar dengan kendala geografis atau penjadwalan dan fleksibilitas dalam kecepatan dan penjadwalan.
Hal ini dapat mendukung berbagai sumber daya pendidikan, mengakomodasi gaya belajar yang beragam , dan menawarkan kesempatan untuk pembelajaran yang dipersonalisasi.
Berikut adalah beberapa manfaat utama pembelajaran online:
- Ini menawarkan fleksibilitas kepada pelajar untuk mengakses materi kursus sesuai kecepatan mereka sendiri.
- Ini memberikan aksesibilitas terhadap pendidikan bagi pelajar dari berbagai lokasi dan mereka yang tidak dapat menghadiri kelas secara fisik.
- Hal ini lebih hemat biaya dibandingkan pengajaran di kelas tradisional, karena mengurangi biaya yang terkait dengan infrastruktur fisik, perjalanan pulang pergi, dan material.
- Hal ini memungkinkan personalisasi yang lebih besar dalam menyesuaikan pengalaman belajar dengan preferensi, kemampuan, dan gaya belajar individu peserta didik.
- Ini mendukung berbagai sumber daya termasuk materi berbasis teks, video, rekaman audio, modul interaktif, e-book, ceramah langsung, dan banyak lagi.
- Ini memiliki jangkauan global yang menghubungkan pelajar dengan instruktur dan rekan-rekan dari seluruh dunia, mendorong pertukaran lintas budaya, kolaborasi, dan paparan terhadap beragam perspektif dan pengalaman.
Disadur dari: www.learnwords.com
Pendidikan
Kemenkes: Pembelajaran Jarak Jauh Pengaruhi Kesehatan Mental Anak
Dipublikasikan oleh Muhammad Armando Mahendra pada 18 Februari 2025
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menilai pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau pembelajaran daring yang dilakukan di masa pandemi COVID-19 berdampak pada kesehatan mental anak, khususnya remaja.
Potret tersebut menggambarkan betapa tingginya permasalahan kesehatan jiwa pada remaja di masa COVID-19 jika tidak diantisipasi dengan cepat, kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Narkoba Kementerian Kesehatan, Fidiansjah saat konferensi pers bersama dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (GTPP). di Graha BNPB, Jakarta, Senin 20 Juli.
Ia mengatakan, besarnya permasalahan terkait kesehatan mental pada masa COVID-19 terlihat dari hasil kajian cepat dampak COVID-19 dan dampaknya terhadap anak Indonesia yang dilakukan oleh organisasi masyarakat Wahana Visi Indonesia pada Mei 2020.
Hasil penelitian menunjukkan, proses belajar mengajar yang dilakukan pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mengakibatkan hanya sekitar 68 persen anak yang memiliki akses terhadap jaringan. Artinya, 32 persen di antaranya tidak mendapatkan fasilitas tersebut, ujarnya.
Dampak dari keterbatasan anak terhadap jaringan menyebabkan mereka belajar mandiri tanpa pendampingan guru. Katanya, hal ini berdampak, yakni sebanyak 37 persen anak tidak tahu kapan harus belajar karena rutin belajar kemudian harus belajar mandiri.
Kemudian, 30 persen diantaranya juga kesulitan memahami pelajaran secara mandiri karena tidak adanya pendampingan dari guru. Sementara itu, 21 persen anak bahkan dinilai belum mampu memahami instruksi guru berdasarkan proses pembelajaran daring.
Selain itu, dampak psikososial pembelajaran yang dilakukan di masa pandemi juga cukup mengkhawatirkan, menurutnya.
“Ada 47 persen anak yang bosan berdiam diri di rumah. Kemudian 35 persen anak khawatir ketinggalan pelajaran karena tidak seperti biasanya, mereka tidak mengikuti pelajaran,” ujarnya.
Selanjutnya, 34 persen anak merasa takut karena COVID-19 meski sudah berada di rumah, dan 20 persen anak merasa rindu bertemu temannya. Sementara itu, 10 persen anak lainnya khawatir dengan menurunnya pendapatan orang tuanya akibat pandemi COVID-19.
Data lain yang disampaikannya juga menyebutkan 11 persen anak mengalami kekerasan fisik karena proses belajar yang tidak biasa. Sementara itu, 62 persen anak juga mengalami pelecehan verbal.
Disadur dari: voi.id
Pendidikan
Berkat Publikasi Ilmiah Versi Nature Index, UI Kembali Raih Top Institutions di Indonesia
Dipublikasikan oleh Muhammad Armando Mahendra pada 18 Februari 2025
Setelah mendapatkan penghargaan awal tahun ini dari The Conversation Indonesia sebagai Institusi Terproduktif karena Penulisan Artikel Ilmiah Populer dari para akademisinya, Universitas Indonesia (UI) kembali dinyatakan sebagai yang terunggul di Indonesia oleh Nature Index. Nature Index adalah open-source database mengenai afiliasi penulis yang bertujuan melacak kontribusi mereka pada sebuah artikel penelitian. Selain unggul di antara institusi pendidikan, UI juga unggul di lembaga riset.
Tahun ini, UI mengalami kenaikan signifikan pada nilai Share (sebaran kontribusi) penelitian, yakni dari 1,18 menjadi 3,52. Nilai Share tersebut diperoleh dari 16 artikel UI di jurnal internasional berkualitas tinggi yang terbit pada periode 1 September 2022–31 August 2023.
Nature Index menetapkan 145 jurnal di bidang ilmu pengetahuan alam dan kesehatan sebagai acuan untuk penilaian artikel riset. Jurnal-jurnal tersebut dipilih berdasarkan reputasinya oleh kelompok peneliti independen.
Sebanyak 16 artikel UI yang merupakan luaran hasil penelitian dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Fakultas Kedokteran, dan Fakultas Teknik, masuk di dalam empat subject riset, yakni Biological Sciences, Chemistry, Health Sciences, dan Physical Sciences. UI mengalami kenaikan nilai Share untuk subject Health Sciences (dari 0,28 menjadi 0,56) dan Physical Sciences (0,8 menjadi 2,85).
Adapun keenam belas artikel tersebut terbit di beberapa jurnal internasional, antara lain Nature, Nature Communications, Neuron, Chemical Communications, Gut, Journal of Infectious Diseases, The Lancet Global Health, The New England Journal of Medicine, ACS Nano, Applied Physics Letters, European Physical Journal C, dan Physical Review B.
Di antara artikel tersebut, artikel berjudul “Strong Lensing and Shadow of Ayon-Beato–Garcia (ABG) Nonsingular Black Hole” yang terbit di jurnal European Physical Journal C memperoleh nilai Share tertinggi. Artikel ini ditulis oleh tim peneliti dari Departemen Fisika, FMIPA UI, dibawah koordinasi Dr. Handika S. Ramadhan.
Selain itu, artikel lain yang berjudul “Towards Precise Constraints in Modified Gravity: Bounds on Alternative Coupling Gravity Using White Dwarf Mass-Radius Measurements”—ditulis oleh tim peneliti yang diketuai oleh Prof. Anto Sulaksono dari Departemen Fisika—memperoleh nilai Share yang tinggi, yakni 0,75.
Menurut Direktur Riset dan Pengembangan UI, Munawar Khalil, S.Si., M.Eng.Sc., Ph.D., Nature Index, dalam pemeringkatannya, tidak hanya menjadikan kuantitas riset sebagai ukuran, tetapi juga melihat seberapa besar kontribusi peneliti dalam sebuah penelitian. Jika sebuah penelitian dikerjakan oleh puluhan peneliti, tentu kontribusi yang diberikan masing-masing peneliti lebih kecil dibandingkan penelitian yang dikerjakan oleh dua atau empat orang. Karena itu, kuantitas bukan menjadi satu-satunya ukuran dalam Nature Index.
“Meski sebuah institusi menerbitkan banyak riset, namun jika kontribusi peneliti kecil, tentu nilai Share-nya juga kecil. Oleh sebab itu, UI terus mendorong para penelitinya agar semakin banyak artikel penelitian yang mampu menembus jurnal-jurnal terbaik dunia, sehingga kontribusi UI di kancah internasional semakin besar,” ujar Khalil.
Disadur dari: ui.ac.id
Pendidikan
Pembelajaran Online Sinkron vs Asinkron: Apa Bedanya?
Dipublikasikan oleh Muhammad Armando Mahendra pada 18 Februari 2025
Kapan pun Anda berada di ruang kelas, bertatap muka dengan instruktur dan teman sekelas, Anda terlibat dalam pembelajaran sinkron. Pembelajaran online sinkron mengacu pada kelas yang berlangsung secara real-time di mana peserta berinteraksi melalui berbagai alat dan platform digital, seperti konferensi video langsung, ruang obrolan, atau ruang kelas virtual.
Di sisi lain, dalam pembelajaran asinkron, siswa terlibat dengan materi pelajaran, ceramah, dan tugas kapan saja dan dari lokasi mana pun, tanpa partisipasi simultan dengan instruktur atau rekan sejawat. Setiap pendekatan menghadirkan manfaat dan tantangan yang unik, dan memahami perbedaan ini dapat membantu Anda mengambil keputusan yang tepat mengenai mode apa yang paling cocok untuk Anda.
Manfaat pembelajaran online sinkron
Pembelajaran online sinkron menawarkan interaksi real-time dari kelas tradisional dengan fleksibilitas tambahan karena jarak jauh. Mode pembelajaran online ini sangat cocok bagi siswa yang ingin terlibat dalam diskusi dinamis, menerima masukan langsung dari instruktur, dan berkolaborasi dengan rekan-rekannya secara real-time dari lokasi mana pun.
1. Interaksi waktu nyata
Salah satu perbedaan utama antara pembelajaran sinkron dan asinkron adalah jenis interaksi antara instruktur dan siswa. Dengan pembelajaran online tersinkronisasi, siswa terlibat satu sama lain dan berpartisipasi aktif dalam lingkungan kelas virtual melalui konferensi video, fungsi obrolan, dan diskusi interaktif.
Bahkan dalam batasan layar komputer, interaksi langsung dan pertukaran informasi langsung menumbuhkan rasa keterhubungan bagi siswa. Mode pembelajaran ini memungkinkan siswa untuk mengajukan pertanyaan kepada profesor dan terlibat dalam aktivitas kolaboratif dengan teman sekelas, sehingga berkontribusi pada pengalaman pendidikan yang mendalam dan responsif.

Sumber: online.njit.edu
2. Bekerja dari mana saja
Pembelajaran online sinkron memungkinkan siswa untuk berpartisipasi dalam kelas dan terlibat dengan materi kursus dari mana saja dengan koneksi internet. Dengan pembelajaran online tersinkronisasi, Anda dapat belajar di mana saja, di kedai kopi, perpustakaan, saat bepergian, atau dalam kenyamanan rumah Anda sendiri.
Fleksibilitas pembelajaran online sinkron memungkinkan pelajar mengakses konten pendidikan dan berinteraksi dengan instruktur dan rekan-rekan terlepas dari lokasi fisik mereka. Fleksibilitas lokasi dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi siswa yang tinggal di daerah yang jauh dan menjamin aksesibilitas bagi mereka yang membutuhkan akomodasi.

Sumber: online.njit.edu
Tantangan pembelajaran online sinkron
Meskipun ada banyak manfaat luar biasa dari pembelajaran online sinkron, beberapa aspek dari mode ini dapat menimbulkan tantangan bagi sebagian siswa. Kekakuan waktu kelas dapat menyebabkan konflik jadwal, dan kemungkinan kesulitan teknis dapat mengganggu pengalaman belajar.
1. Jadwal terstruktur
Jika Anda mempertimbangkan untuk mengambil kursus online sinkron, Anda harus mengikuti jadwal yang terstruktur. Dengan pembelajaran online sinkron, kelas diadakan pada waktu tertentu serupa dengan kelas tatap muka tradisional. Misalnya, Anda mungkin mengadakan kelas yang diadakan dua kali seminggu di platform konferensi video seperti Zoom , dan kehadiran akan diperhitungkan.
Memiliki waktu pertemuan kelas yang telah ditentukan dapat bermanfaat karena memberikan rasa rutinitas dan disiplin bagi siswa. Jika Anda mencari jadwal terstruktur dengan fleksibilitas belajar dari rumah, pembelajaran online sinkron dapat menjadi keseimbangan yang baik untuk Anda. Jadwal terstruktur dapat membantu Anda tetap teratur, bertanggung jawab, dan terlibat secara aktif di kelas.
Namun, menetapkan waktu pertemuan kelas dapat menyulitkan siswa dengan jadwal yang bertentangan atau bagi siswa yang berada di zona waktu berbeda. Waktu pertemuan yang spesifik dapat menjadi tantangan tersendiri bagi mereka yang memiliki banyak tanggung jawab, seperti komitmen pekerjaan dan keluarga. Selain itu, bagi siswa yang tinggal di zona waktu berbeda, kelas sinkron yang diadakan pada jam-jam yang tidak tepat dapat mempersulit partisipasi.
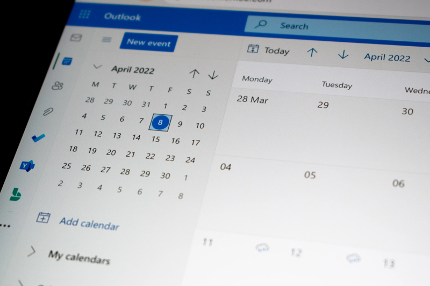
Sumber: online.njit.edu
2. Masalah teknis
Keterlambatan video, masalah konektivitas audio, dan layar macet adalah kejadian umum dalam pembelajaran online dan dapat berdampak besar pada pengalaman belajar siswa. Dengan pembelajaran online yang sinkron, instruktur dan siswa perlu menggunakan keterampilan teknis mereka untuk mengatasi masalah selama panggilan video, seperti gema audio, internet yang tidak stabil, serta masalah perangkat lunak dan perangkat keras. Memiliki akses koneksi internet yang memadai dan perangkat yang berfungsi sangat penting untuk pembelajaran dalam mode pembelajaran ini karena semua sesi kelas, tugas, dan materi disediakan secara virtual.
Manfaat pembelajaran online asinkron
Berbeda dengan pembelajaran sinkron, pembelajaran asinkron tidak memerlukan interaksi waktu nyata. Dengan pembelajaran online asinkron , siswa dapat terlibat dengan materi kelas pada waktu mereka sendiri.
1. Sangat fleksibel
Pembelajaran online asinkron adalah mode pembelajaran yang paling fleksibel karena memungkinkan siswa untuk bekerja dengan kecepatan mereka sendiri dari lokasi mana pun. Meskipun tenggat waktu tugas tetap harus dipatuhi, siswa dapat mengakses materi pelajaran, perkuliahan, dan tugas sesuai keinginan mereka.
Fleksibilitas ini memungkinkan pelajar untuk menyeimbangkan kegiatan akademis mereka dengan pekerjaan, komitmen keluarga, dan tanggung jawab lainnya. Anda akan dapat menyesuaikan pembelajaran Anda dengan pekerjaan dan kehidupan pribadi Anda. NJIT memiliki lebih dari 40 program online untuk dipilih sehingga Anda bisa mendapatkan gelar STEM terbaik dengan fleksibilitas pembelajaran online dan memajukan karir Anda.

Sumber: online.njit.edu
2. Skalabel dan hemat biaya
Kualitas lain yang menjadikan pembelajaran online asinkron menguntungkan adalah skalabilitas dan efektivitas biayanya. Platform pembelajaran asinkron dapat menampung sejumlah besar siswa secara bersamaan, sehingga memungkinkan universitas memberikan siswa akses yang lebih besar ke kelas-kelas ini. Skalabilitas dan efektivitas biaya ini berkontribusi pada aksesibilitas dan keterjangkauan pendidikan tinggi, sehingga lebih mudah dijangkau oleh siswa dari berbagai latar belakang dan status sosial ekonomi.
Tantangan pembelajaran online asinkron
Pembelajaran online asinkron dapat menjadi tantangan karena, karena sifatnya yang online, kurangnya interaksi dengan dosen dan teman sejawat. Selain itu, melawan gangguan, mengatasi penundaan, dan tetap fokus semuanya memerlukan tingkat disiplin dan keterampilan manajemen waktu, yang penting untuk pembelajaran asinkron.
1. Interaksi Terbatas
Meskipun Anda akan mendapatkan manfaat dan fleksibilitas belajar kapan saja dan di mana saja, dengan kurangnya interaksi real-time, pembelajaran asinkron mungkin tampak seperti pengalaman yang terisolasi bagi sebagian orang. Pembelajaran asinkron sangat cocok bagi mereka yang senang bekerja secara mandiri. Namun, membentuk koneksi pribadi dan jaringan dengan orang lain juga bisa menjadi lebih menantang.
Tidak adanya komunikasi tatap muka dapat menimbulkan perasaan terasing dari kelas dan menyulitkan siswa untuk terhubung dengan instrukturnya. Penting untuk memanfaatkan jam kerja instruktur Anda , berpartisipasi dalam forum diskusi, dan berkolaborasi dengan siswa lain untuk menumbuhkan rasa keterhubungan.

Sumber: online.njit.edu
2. Manajemen waktu
Pembelajaran asinkron memerlukan sejumlah besar disiplin dan keterampilan manajemen waktu untuk mengimbangi beban kursus, yang dapat menjadi tantangan bagi sebagian pelajar. Pembelajar asinkron harus mengambil inisiatif dalam mencari klarifikasi, mengeksplorasi sumber daya, dan terlibat dengan konten kursus secara mandiri. Selain itu, karena sebagian besar siswa pembelajaran online asinkron harus menjalankan tanggung jawab di luar kelas, manajemen waktu yang efektif sangat penting untuk menyeimbangkan pekerjaan, akademik, dan kehidupan.

Sumber: online.njit.edu
Disadur dari: online.njit.edu